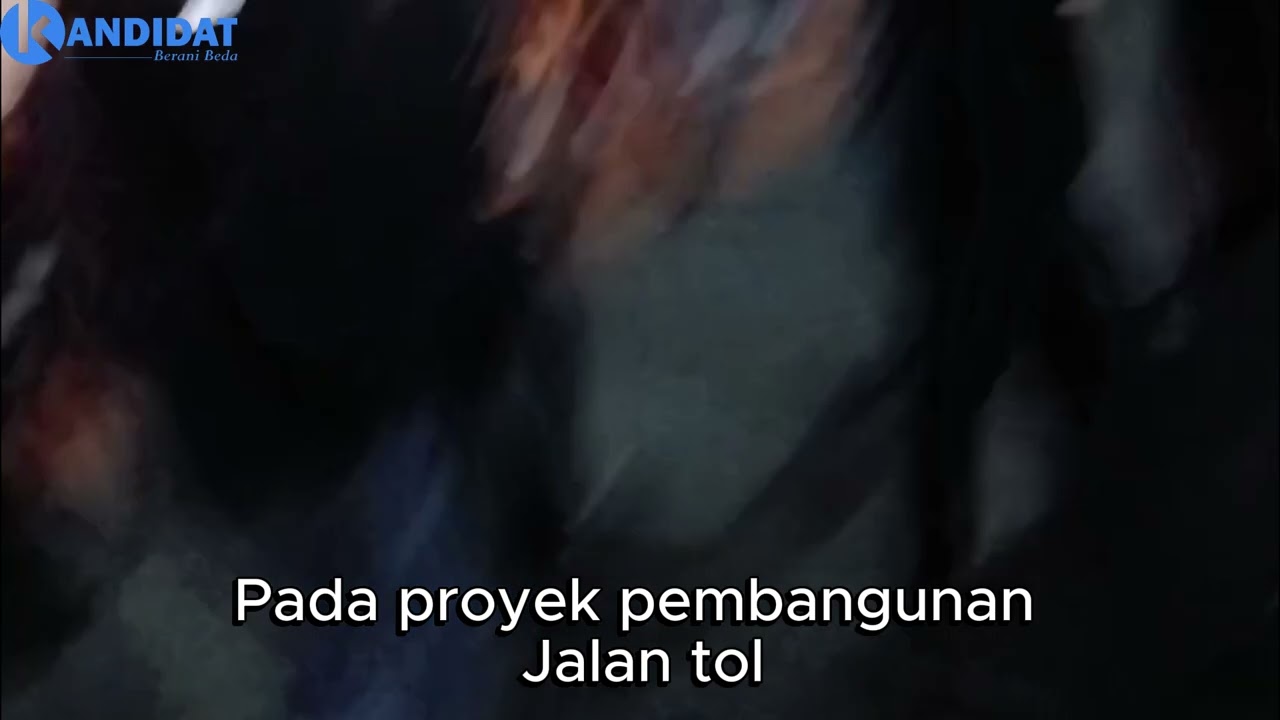HARIANKANDIDAT.CO.ID - Program Reforma Agraria yang seharusnya menata ulang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara adil di Indonesia dinilai gagal dijalankan di Provinsi Lampung.
Hal ini terlihat dari perubahan fungsi tanah adat milik Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir (MBPPI) Negara Batin, Way Kanan, yang semula diperuntukkan sebagai hutan lindung, kini beralih menjadi hutan produksi melalui skema Hutan Tanaman Industri (HTI).
Penilaian itu disampaikan Penasihat Hukum sekaligus Kuasa Hukum Penyimbang MBPPI, Gindha Ansori Wayka pengacara ii menyebut, tanah adat yang telah diserahkan oleh tokoh adat Umpu Tuyuk pada tahun 1940 untuk kepentingan pelestarian hutan, sejak 1996 dialihkan menjadi kawasan Hutan Register dan dikelola oleh perusahaan negara.
“Tanah adat itu diberikan untuk hutan larangan, tapi sejak 1996 berubah menjadi hutan tanaman industri, dikelola oleh PT Inhutani V. Reforma Agraria yang digadang-gadang untuk keadilan justru menghilangkan hak masyarakat adat,” ujar Gindha.
Kawasan yang dimaksud mencakup dua hutan register besar, yaitu Register 44 Sungai Muara Dua dan Register 46 Way Hanakau, yang pengelolaannya diberikan kepada PT Inhutani V berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 398/Kpts-II/1996. Namun, menurut Gindha, sejak izin diterbitkan, perusahaan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat adat MBPPI.
“Selama hampir tiga dekade, tidak ada manfaat yang dirasakan masyarakat adat. Bahkan, warga MBPPI tidak tinggal di kawasan tersebut, justru yang mendiami adalah para perambah dari luar daerah,” tambahnya.
Gindha juga menyoroti tidak adanya tindak lanjut terhadap Surat Menteri Kehutanan Nomor: 427/Menhut-VIII/2001 yang meminta pengembalian tanah ulayat masyarakat adat kepada Gubernur Lampung. Surat tersebut juga memerintahkan pola kemitraan antara masyarakat adat dan perusahaan pengelola, namun hingga kini tidak ada kesepakatan yang terjadi.
“Pola kemitraan yang dimaksud bukan dengan warga perambah, melainkan dengan masyarakat adat pemilik sah tanah tersebut. Sayangnya, tidak ada satupun perusahaan yang merespons surat itu,” tegas Gindha, yang juga akademisi di salah satu perguruan tinggi swasta di Lampung.
Lebih lanjut, Gindha menduga negara turut dirugikan dalam pengelolaan HTI ini karena pendapatan yang disetor kepada PT Inhutani V dari para penggarap atau perusahaan rekanan disebut hanya berkisar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per hektar per tahun.
“Dengan luas konsesi mencapai 55 ribu hektar, izin ini patut dievaluasi bahkan dicabut. Negara semestinya mendapat pemasukan yang layak, bukan membiarkan kerugian karena lahan dikuasai perambah dan pengelolaan tidak maksimal,” jelas mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Pidana FH Unila ini.
Menanggapi penerbitan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan oleh Presiden Prabowo Subianto, Gindha menilai aturan ini bisa menjadi alat hukum untuk membongkar penguasaan lahan ilegal di kawasan hutan, meski belum menyentuh hak-hak masyarakat adat secara langsung.
“Perpres ini penting sebagai landasan untuk menertibkan kawasan, tapi seharusnya juga melibatkan masyarakat adat dalam proses negosiasi dengan perambah, karena merekalah pemilik asli lahan ini sejak awal,” pungkas Gindha. (rls)